My Diary Chapter 9 : Mendung
Story Edelweiss – Hari ini, 14:30, mendung menggantung seperti selimut abu-abu yang menekan langit. Aku duduk di kursi kayu tua di depan toko tempatku bekerja, tongkrongan kecil yang sudah jadi saksi banyak cerita yang tak pernah benar-benar kuceritakan pada siapa pun. Angin sore membawa bau aspal basah, meski hujan belum turun. Udara sejuk menampar pelan kulitku, seperti mengingatkan bahwa dunia selalu punya cara untuk menenangkan, bahkan ketika hati sedang berisik. Ada suara motor lewat, gemerincing koin dari warung sebelah, dan sesekali tawa anak-anak yang masih berani main kelereng meski awan menakut-nakuti mereka dengan warna gelapnya. Semuanya biasa, tapi entah kenapa sore ini terasa seperti lembaran yang lebih berat, seakan setiap detik memanjang dan menatapku balik, menantangku untuk jujur pada diri sendiri.
Hai—lagi-lagi aku ingin menyapamu dengan kata itu. “Apa kabar?” Pertanyaan yang begitu sederhana, nyaris klise, tapi selalu punya denting yang sama di dadaku setiap kali terlintas. Aku tahu, mungkin kamu baik-baik saja. Mungkin kamu bahkan sedang tertawa di tempat lain, dengan orang-orang yang membuatmu lupa ada seseorang di sini yang masih mengingatmu seperti mengingat aroma kopi yang menguap dari cangkir hangat di pagi hari. Tapi tetap saja, rasanya seperti keharusan bagiku untuk bertanya. Ada sesuatu yang aneh dalam kebiasaan itu, seperti doa kecil yang tidak pernah usai, doa yang selalu kusebut meski aku sendiri ragu apakah kamu pernah mendengarnya.
Baca Juga : My Diary Chapter 8 : Rintik Rindu
Pagi tadi aku berlari—kebiasaan yang kupikir bisa menipiskan segala yang menumpuk di kepala. Sepuluh kilometer. Lima kilometer pertama kuhabiskan dengan ritme yang biasa, kaki menapak aspal, napas membentuk awan kecil di udara dingin. Sisanya, jujur saja, lebih banyak jalan daripada lari. Perutku protes, mungkin karena akhir-akhir ini aku sering telat makan. Masuk angin, kata orang. Tapi aku lebih suka menyebutnya: tubuh yang menagih janji, tubuh yang mengingatkan bahwa aku terlalu sibuk menghindari rasa sepi sampai lupa merawat diri. Setiap langkah di jalan itu seperti mengetuk pintu kenangan—dan selalu, entah bagaimana, bayanganmu ikut berlari di sampingku. Bukan nyata, tapi cukup untuk membuatku melirik ke sisi kiri, seolah kamu ada di sana, senyum kecil di bibirmu yang selalu berhasil membuat dunia terasa lebih sederhana.
Kalau kamu, ke mana minggu ini? Ke pantai lagi, seperti waktu itu ketika kita tertawa karena pasir menempel di sepatu yang baru dibeli? Atau kamu jalan-jalan ke CFD, menembus lautan orang yang berdesakan mencari udara segar? Atau mungkin kamu hanya duduk di warung kecil, menikmati semangkuk seblak pedas yang uapnya mengaburkan kacamata? Pertanyaan itu melayang seperti daun kering, tak pernah mendarat, karena aku tak pernah benar-benar tahu jawabannya. Aku hanya bisa menebak, menulis kemungkinan-kemungkinan yang tak pernah bisa kupastikan. Dan di situlah rindu bekerja: ia menjahit celah ketidaktahuan dengan benang imajinasi, membentuk gambaran yang mungkin tak pernah sama dengan kenyataan.
Hari-hari berlalu, dan tetap saja rasanya seperti kemarin ketika semua ini dimulai. Waktu adalah penipu ulung; ia berjalan, tapi meninggalkan jejak yang tak pernah pudar. Rasa ini—ah, rasa ini—seperti hujan yang tak kunjung reda di hati, meski matahari sudah lama muncul di luar. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, mengapa rindu selalu menemukan jalan pulang, meski pintu sudah kututup rapat-rapat? Mungkin karena kamu adalah rumah yang tak pernah benar-benar bisa kutinggalkan.
Baca Juga : My Diary Chapter 7 : Kilometer Rindu
Maaf kalau aku masih terus merindukanmu. Kadang, aku merasa seperti bayangan yang tak diundang, seperti angin yang datang membawa debu ke jendela rumahmu. Aku khawatir, apakah ini mengganggumu? Apakah namaku pernah muncul tiba-tiba di benakmu dan membuatmu mendesah kesal? Jika iya, izinkan aku meminta maaf, walau aku tak tahu apakah maafku sampai atau hanya terhenti di udara seperti asap dupa yang hilang ditelan angin.
Ada begitu banyak cerita yang ingin kubagi, begitu banyak hal kecil yang ingin kuceritakan. Tentang es jeruk yang rasanya terlalu asam pagi ini, tentang kucing liar yang tiba-tiba bersandar di kakiku kemarin, tentang mimpi aneh di mana kita berjalan di hutan dan tertawa tanpa alasan. Tapi aku menahan semuanya, menumpuknya di halaman-halaman diam yang hanya kubaca sendiri. Kadang aku membayangkan, bagaimana rasanya kalau kita bisa kembali seperti dulu—saat kita hanya dua orang asing yang tertawa karena hal-hal konyol, saat kata “cinta” belum sempat menyelinap di antara kita. Ada kehangatan dalam bayangan itu, kehangatan yang membuatku ingin berhenti sejenak dan mengulang semuanya.
Aku tahu, waktu tak bisa diputar. Kita tak bisa benar-benar kembali ke awal. Tapi jika ada sedikit celah, sedikit kesempatan, aku ingin… aku ingin kita bisa bertemu lagi tanpa beban. Mungkin aku bodoh karena menunggu sesuatu yang tak pasti, tapi jika menunggu itu artinya menunggumu, maka aku rela. Waktu bukan musuh bagiku, selama di ujungnya ada bayanganmu yang samar. Menunggu bukan hukuman jika hadiahnya adalah melihat senyummu sekali lagi.
Baca Juga : My Diary Chapter 6 : Tentang Gunung dan Lautan
Di depan toko ini, sore yang mendung terus memeluk langit. Lampu-lampu jalan belum menyala, tapi cahaya sudah menipis. Seperti hatiku, mungkin, yang terus mengandalkan sisa-sisa terang untuk bertahan. Aku mendengar suara rintik kecil, entah itu hujan atau hanya daun yang jatuh menimpa atap seng. Aroma tanah basah mulai menanjak, tajam dan manis sekaligus. Ada keheningan yang aneh, keheningan yang tidak kosong. Seperti menunggu sesuatu, seperti dunia ikut menahan napas.
Kadang aku berpikir, mungkin rindu itu seperti cuaca sore ini—tak bisa ditebak. Pagi bisa panas terik, siang jadi mendung pekat, dan sebelum sempat menyiapkan payung, hujan turun begitu saja. Begitu pula perasaanku padamu. Aku bisa saja sibuk, bisa saja tertawa dengan teman-teman, lalu tiba-tiba ingatan tentangmu datang seperti awan hitam yang menutup langit. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan. Hanya datang dan menetap. Dan aku? Aku hanya bisa menerima, seperti bumi menerima hujan.
Aku menulis ini bukan untuk mengikatmu. Bukan juga untuk mengulang luka. Aku menulis karena hanya ini yang bisa kulakukan agar kamu tetap ada, meski hanya dalam huruf-huruf yang kutata. Kamu mungkin tak akan pernah membaca, mungkin tak akan pernah tahu. Tapi ada sesuatu yang ajaib dalam menulis: seolah-olah setiap kata yang tergores adalah cara lain untuk memelukmu, dari jauh, diam-diam.
Baca Juga : My Diary Chapter 5 : Sebuah Perenungan
Sore semakin gelap. Lampu toko tetangga satu per satu menyala, menciptakan bintik-bintik cahaya di jalanan basah. Orang-orang bergegas pulang, membawa payung dan jaket. Aku masih di sini, duduk, menatap jalan yang kini memantulkan cahaya seperti kaca. Di sela langkah-langkah yang hilang, aku mendengar detak hatiku sendiri—ritme yang entah sejak kapan selalu menyebut namamu. Dan aku tahu, malam ini aku akan kembali menulis, kembali berlari, kembali menanyakan kabarmu dalam doa yang sama.
Jadi, apa kabar, kamu yang jauh di sana? Semoga langit yang menaungimu juga penuh cerita. Semoga kamu tetap hangat, tetap tertawa, tetap bahagia. Jika suatu hari, entah kapan, kita bertemu lagi, aku harap dunia masih mengizinkanku untuk menyapamu dengan sederhana: “Hai, apa kabar?” Karena di balik kata-kata itu, ada seluruh semesta rindu yang tak pernah benar-benar bisa kujelaskan, bahkan dalam seribu kata sekalipun.
Minggu, 21 September 2025















Share this content:


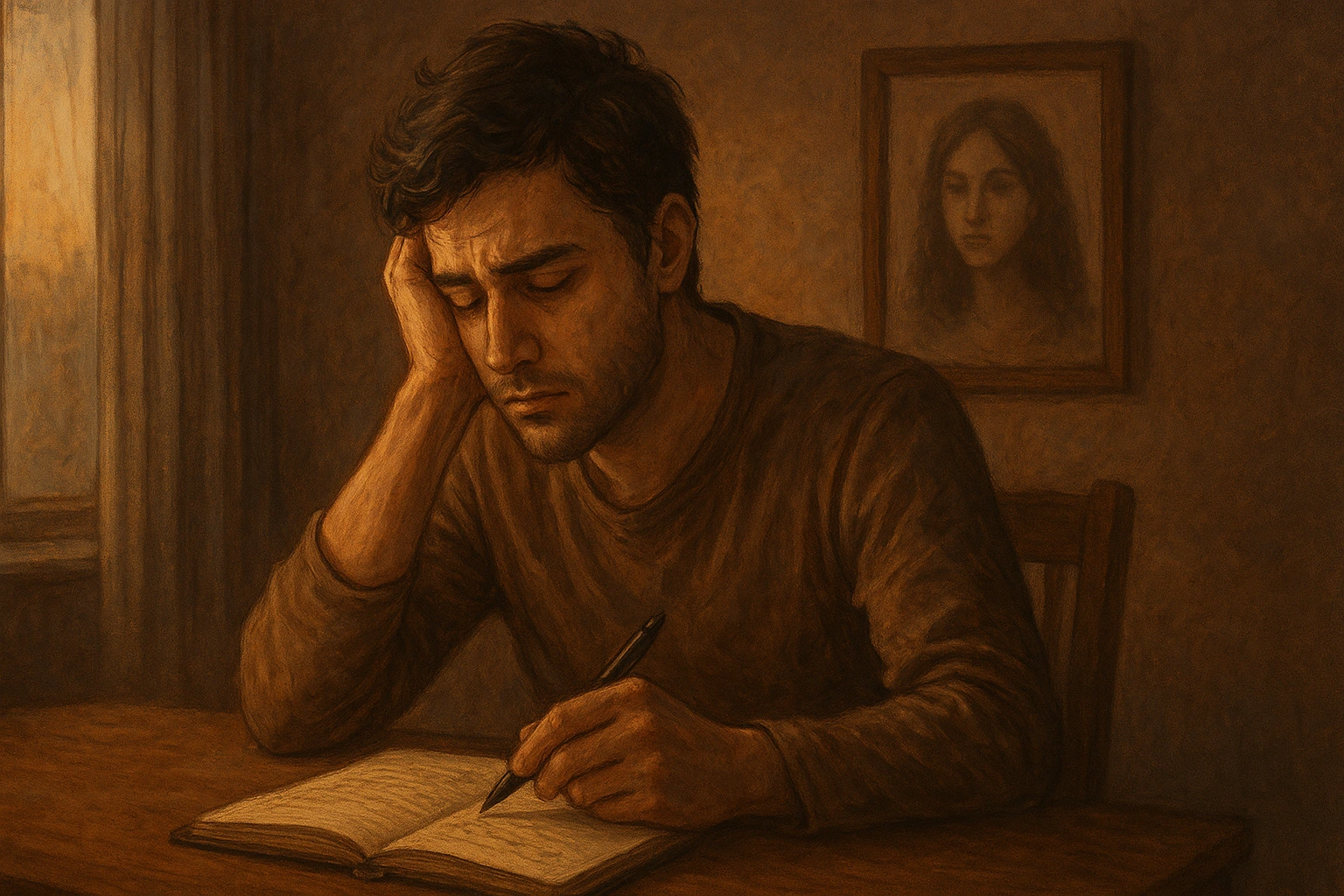
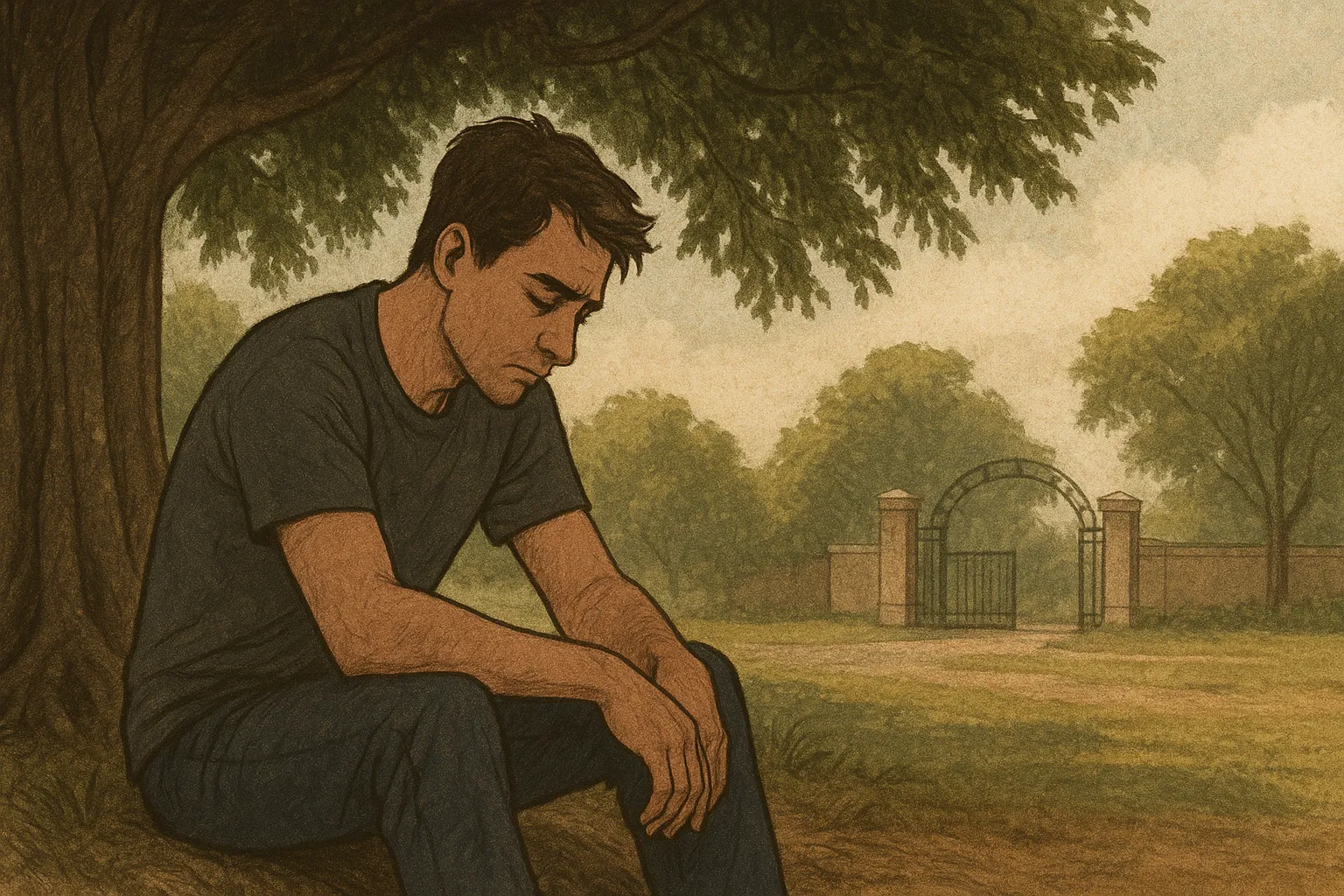










Post Comment