My Diary Chapter 1 : Titipan Rindu Dari Kota Malang
Hai kota Malang,
Malam ini aku kembali menulis, seperti seorang lelaki yang mencari tempat untuk menitipkan rindu. Bukan rindu yang bisa disampaikan secara terang-terangan, melainkan rindu yang harus kuselipkan di antara dinginmu yang menggigilkan tulang, dan di antara rintik hujanmu yang jatuh pelan, seperti nada-nada piano yang dimainkan tanpa penonton. Malang, aku selalu merasa kau adalah semacam perantara. Seakan-akan kau punya kemampuan menyimpan pesan, lalu menyampaikannya pada seseorang yang aku tuju. Kau, dengan kabutmu, dengan hujanmu, dengan anginmu yang mendesirkan daun-daun, selalu berhasil membuatku percaya bahwa rinduku tidak pernah hilang, hanya berpindah tempat—dari dadaku ke pelukanmu.
Pagi di kotamu selalu dingin, tapi aku menyukainya. Dinginmu seperti cara lembut alam menepuk pundak: mengingatkan bahwa dunia masih berjalan meski hati sering berhenti sejenak untuk bernostalgia. Aku suka cara embun menggantung di ujung daun, seolah ikut menahan air mata yang seringkali tak jadi jatuh dari mataku. Aku titipkan rinduku di sana, pada embun itu, pada dingin itu. Aku ingin ia menjelma jadi pesan yang sampai padanya, seseorang yang kini jauh dariku, tapi tak pernah benar-benar hilang dari pikiranku.
Aku sedang menunggu hari di mana kita bisa saling berkomunikasi lagi. Rasanya seperti menunggu hujan reda ketika sudah terlanjur basah kuyup—tidak ada kepastian kapan langit akan berbaik hati, tapi ada keyakinan bahwa hujan tidak akan abadi. Waktu memang punya cara yang misterius. Ia bisa mempertemukan orang di persimpangan paling tak terduga, lalu memisahkan mereka di titik yang tak pernah direncanakan. Namun, aku percaya pada perputarannya; jika jarum jam selalu kembali ke angka dua belas, mungkin begitu juga aku dan dia—selalu ada kesempatan untuk kembali, meski harus menunggu jarak yang panjang.
Dan untukmu kota Banyumas, setiap sudutmu seakan menyimpan potongan memoriku dengannya. Jalan-jalan yang basah selepas hujan seperti mengingatkan langkah kami yang pernah seirama. Aroma kopi yang mengepul dari warung kecil di tepi jalan, menyalakan lagi tawa yang dulu sempat kami bagi. Dan langitmu—ah, langitmu selalu jadi lembaran kosong tempat aku menulis doa. Aku menatap birumu, berharap ia juga sedang menatap langit yang sama di tempatnya kini. Bukankah langit itu luas, tapi tetap satu? Seperti hatiku yang penuh dengan jarak, tapi tetap hanya tertuju padanya seorang.
Kadang aku merasa rindu ini seperti asap rokok yang kuhembuskan. Ia naik perlahan, menari-nari di udara, sebelum akhirnya hilang. Tapi siapa sangka, bahkan asap itu meninggalkan aroma, meninggalkan jejak di pakaian, meninggalkan sisa yang menempel meski sudah berlalu. Begitu juga aku—meski jarak ini menjauhkan kami, meski waktu membuat komunikasi terputus, aku tahu ada sisa-sisa yang tertinggal. Sisa yang tak pernah bisa dihapuskan begitu saja.
Aku sering menulis di buku ini bukan karena aku pandai menyusun kata, tapi karena aku takut jika aku diam, rinduku akan membusuk di dalam dada. Menulis adalah caraku membuka jendela kecil di hatiku, agar rindu ini bisa keluar meski perlahan. Kadang aku merasa seperti sedang berbicara langsung padanya lewat tinta—bahwa setiap huruf yang kutorehkan akan sampai padanya, meski ia tak pernah membaca. Entah kenapa, aku percaya pada hal-hal sederhana semacam itu.
Malam-malamku di sini sering ditemani oleh hujan yang jatuh deras di atap rumah. Suaranya bagai tepukan tangan alam semesta, seakan sedang menertawakan aku yang masih setia menunggu pesan yang tak kunjung datang. Tapi aku tak marah. Aku justru menemukan ketenangan dalam derai itu. Karena hujan selalu mengingatkanku padanya—caranya berbicara, caranya tertawa, bahkan caranya diam. Hujan adalah rekaman paling lengkap tentang dirinya. Dan setiap kali aku mendengar rintiknya, aku merasa ia hadir di sebelahku, meski hanya sebatas bayangan.
Ada kalanya aku ingin menyerah. Aku ingin menutup buku ini, membuang semua catatan yang penuh dengan namanya, dan berpura-pura hidup seperti biasa. Tapi selalu ada sesuatu yang menahanku. Rasa itu terlalu besar untuk dikubur begitu saja. Ia seperti akar pohon yang sudah terlanjur meranggas ke segala arah, mustahil dicabut tanpa meruntuhkan tanahnya. Rasa itu sudah jadi bagian dariku. Jadi meski aku mencoba melupakannya, aku hanya akan melupakan diriku sendiri.
Banyumas, aku iri padamu. Kau bisa menemuinya kapan saja. Kau bisa menyapanya lewat hujanmu, mengusapnya lewat dinginmu, menemaninya lewat langitmu. Sementara aku hanya bisa menatapmu dari jauh, berharap kau sudi menjadi jembatan antara aku dan dirinya. Katakan padanya bahwa aku tidak pernah benar-benar pergi. Bahwa aku masih di sini, menunggu, seperti orang yang menunggu matahari terbit setelah malam yang panjang.
Aku ingin sekali lagi duduk di bangku panjang kotamu, di bawah pohon yang rindang, dengan segelas es jeruk. Aku ingin sekali lagi mendengar suaranya bercampur dengan riuh jalanan, sekali lagi melihat senyumnya yang mengalahkan lampu-lampu kota. Tapi itu semua masih sebatas keinginan, sebatas doa yang kuletakkan di langitmu. Aku tidak tahu kapan akan terkabul, tapi aku tahu aku tidak akan berhenti berharap.
Aku menulis ini sebagai catatan, bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Jika suatu hari ia kembali, aku ingin ia tahu bahwa aku tidak pernah berhenti menunggu. Bahwa aku menuliskan namanya di setiap embun pagi, di setiap rintik hujan sore, di setiap bintang malam. Bahwa aku menitipkan rinduku padamu, Malang, agar kau sampaikan kepadanya dengan cara yang paling lembut, paling indah, paling jujur.
Dan jika suatu hari aku tidak sempat lagi menulis, aku berharap rinduku tetap tersimpan di udara kotamu. Karena aku percaya, rindu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah bentuk—kadang menjadi hujan, kadang menjadi angin, kadang menjadi langit biru yang luas. Dan setiap kali ia menatapnya, aku ingin ia tahu: aku masih di sini.
Selamat malam, kota Malang. Dan untukmu Banyumas, Jagalah rinduku. Jagalah namanya. Sampaikan salamku padanya jika suatu hari ia kembali melewati jalan-jalanmu. Katakan padanya bahwa aku masih menunggu, selalu menunggu, sampai hari itu tiba—hari ketika kita akhirnya bisa saling berkomunikasi lagi.
Malang, 23 Agustus 2025
Share this content:


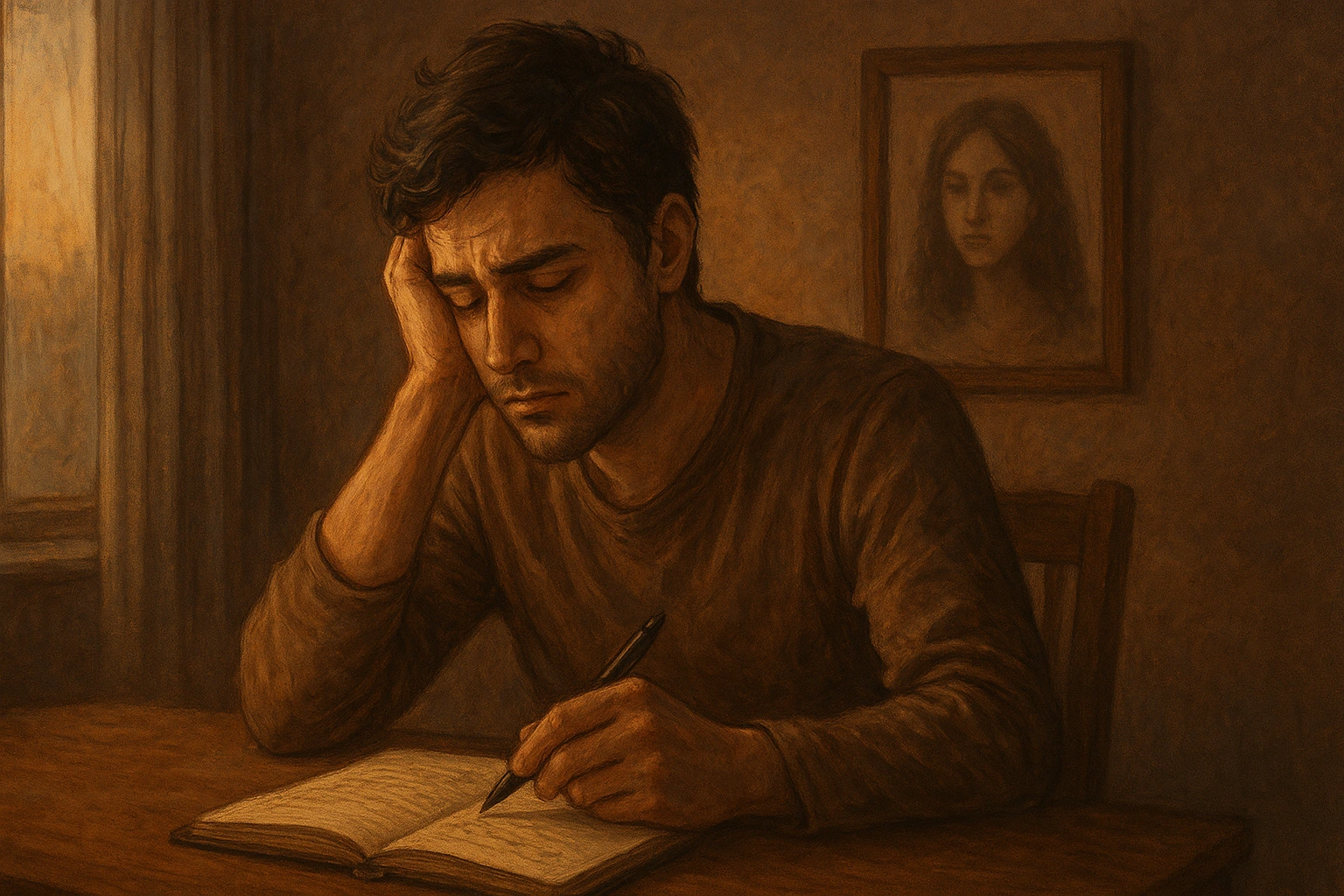
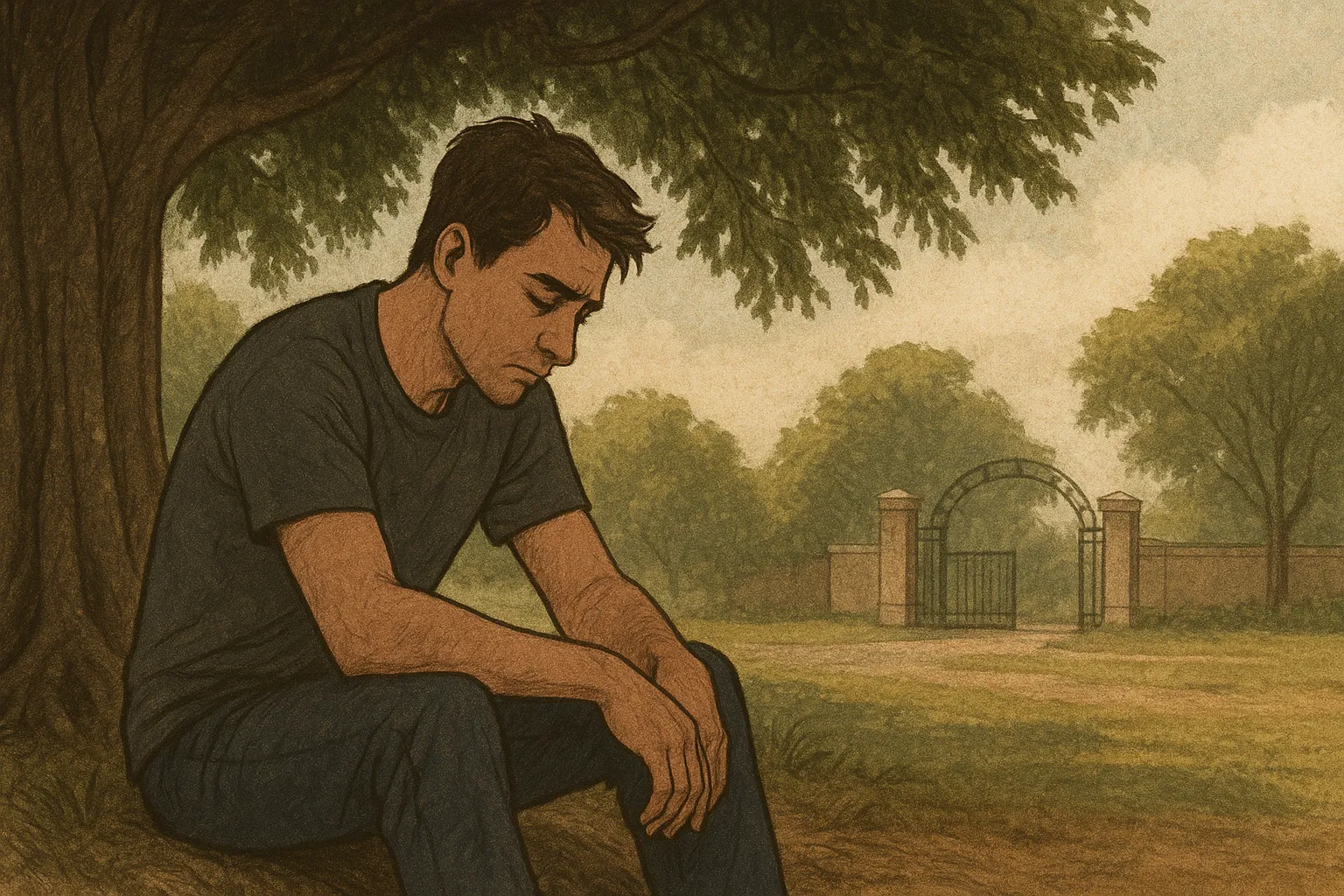










Post Comment