Fiksi
Prosa
Catatan Perjalanan, Cerita Kota Malang, Diary Seorang Laki-Laki, Edelweiss, Inspirasi Kehidupan, Kehidupan Di Malang, Kehidupan Sederhana, Keramaian Orang Asing, Ketenangan Batin, Kota Malang, Monolog Kota Malang, Perjalanan Hidup, Perjalanan Jiwa, Refleksi Diri, Story Edelweiss, Suasana Kota Malang, Wisata Malang
Admin
0 Comments
My Diary Chapter 3 : Tentang Kota Malang
Story Edelweiss – Hari ini aku kembali menulis, menumpahkan isi kepala yang berisik dengan kata-kata yang barangkali hanya aku sendiri yang akan membacanya. Entah sudah berapa lama aku di kota ini, Malang—kota yang sebenarnya tak ada hubungannya denganku sebelumnya, kota yang tak punya kenangan masa lalu, tak ada seseorang yang spesial menungguku, dan tak ada alasan besar yang membuatku harus jatuh cinta kepadanya. Namun, anehnya, aku justru menemukan semacam kedamaian yang tak pernah kutemukan di tempat lain. Malang, dengan segala ketidaksengajaan, menjadi semacam ruang singgah yang membuatku merasa lebih hidup, walau tak ada yang benar-benar mengenal siapa aku.
Aku sering berpikir, mungkin aku hanyalah pengembara yang lelah dengan hiruk pikuk orang-orang yang terlalu mengenal namaku. Karena anehnya, aku lebih merasa diterima di tengah keramaian orang asing, dibandingkan berada di tengah-tengah orang yang pura-pura mengerti tentangku. Di sini, di Malang, aku seperti butir pasir di antara ribuan butir lainnya—tak ada yang istimewa, tak ada yang terlihat berbeda, tapi justru itulah yang membuatku bebas. Tak ada tatapan menilai, tak ada bisik-bisik yang mencoba menebak isi kepalaku, dan tak ada nama yang dipanggil dengan maksud terselubung.
Baca Juga : My Diary Chapter 1 : Titipan Rindu Dari Kota Malang
Aku masih ingat ketika pertama kali menyusuri jalan-jalan kecil di kota ini. Ada sapaan ramah dari tukang parkir yang bahkan tak tahu siapa aku, ada ucapan terima kasih dari pedagang kaki lima yang barangnya kubeli, ada senyum sederhana dari orang yang berpapasan denganku di trotoar. Semua terasa begitu ringan, begitu tulus. Mereka tak peduli siapa aku, dari mana aku berasal, atau apa yang aku sembunyikan. Semua interaksi itu singkat, nyaris tak berarti bagi sebagian orang, tapi bagiku itu seperti pelukan kecil yang menguatkan hati yang rapuh.
Jika ada yang bertanya, apakah aku sedang mencari pelarian, aku tak akan membantah. Mungkin benar, aku memang melarikan diri. Tapi bukan lari dari kenyataan, melainkan lari untuk menemukan kembali diriku sendiri. Ada kalanya lingkungan yang terlalu mengenal kita justru membuat kita kehilangan jati diri. Mereka terlalu sering berkata, “Aku tahu siapa kamu,” padahal sejujurnya, mereka hanya tahu apa yang tampak di permukaan. Sedangkan orang asing, dengan ketidaktahuannya, justru membebaskan kita dari beban topeng yang melelahkan.
Kadang aku berpikir, ketidaktahuan itu jauh lebih indah daripada sok tahu. Karena sok tahu seringkali melahirkan prasangka, sementara ketidaktahuan justru membuka ruang untuk keikhlasan. Bukankah begitu? Aku sering merasa lebih damai ketika orang asing tersenyum padaku tanpa perlu tahu ceritaku. Senyum itu terasa jujur, tidak dipengaruhi oleh masa lalu, tidak dipengaruhi oleh gosip, dan tidak dibebani ekspektasi.
Baca Juga : My Diary Chapter 2 : Berbagi Cerita
Malang, dengan hawa dinginnya di pagi hari, seperti sedang mengajakku berdamai dengan diri sendiri. Udara yang menyusup lewat celah jaketku mengingatkanku bahwa hidup tak selalu harus berlari. Ada waktunya kita berhenti sejenak, menghirup udara dalam-dalam, lalu membiarkan diri kita merasa tenang tanpa harus memikirkan apa kata orang. Kadang aku duduk di sebuah kafe kecil di sudut jalan, hanya untuk mendengarkan suara kendaraan lewat, celotehan anak muda yang bercanda, atau bahkan suara hujan yang menepuk-nepuk atap. Dari sana aku merasa: mungkin inilah yang disebut kebahagiaan sederhana.
Aku bukan orang yang menyukai keramaian, setidaknya bukan keramaian yang penuh basa-basi. Tapi anehnya, keramaian orang asing itu terasa menenangkan. Seperti berada di tengah laut, mendengar debur ombak yang bergantian memukul pantai. Mereka ramai, tapi tak mengusikku. Mereka hidup dengan urusannya sendiri, tanpa mencoba memasuki ruang pribadiku. Ada jarak yang aman, tapi tetap hangat.
Terkadang aku berjalan di sekitar alun-alun kota. Di sana ada keluarga kecil yang tertawa bersama, ada pasangan muda yang saling menggenggam tangan, ada anak-anak yang berlari mengejar balon. Aku tidak mengenal satu pun dari mereka, tapi pemandangan itu seperti obat bagi batinku. Seolah aku sedang menonton sebuah film kehidupan yang nyata, di mana aku boleh menjadi penonton tanpa harus ikut bermain peran. Dan itu menyenangkan, karena untuk sekali ini, aku tak perlu berpura-pura kuat, tak perlu tersenyum hanya untuk menyenangkan orang lain. Aku cukup menjadi diriku sendiri, seorang asing di tengah keramaian.
Kadang aku tertawa kecil pada diriku sendiri. Dulu, aku kira ketenangan hanya bisa ditemukan di tempat sunyi, di gunung, atau di tepi pantai yang sepi. Tapi nyatanya, ketenangan justru kutemukan di tengah keramaian orang asing, di jalanan kota Malang yang penuh lalu-lalang. Rupanya ketenangan bukan tentang sepi, melainkan tentang bebas dari penilaian.
Di kota ini, aku belajar bahwa rumah bukan hanya soal tempat kita dilahirkan atau dibesarkan. Rumah bisa saja menjadi kota asing, jalan asing, bahkan orang asing yang menatapmu dengan senyum sederhana. Rumah adalah tempat di mana kita merasa diterima, tanpa syarat, tanpa beban. Dan entah kenapa, Malang memberi itu padaku.
Mungkin orang lain tak akan mengerti kenapa aku begitu betah di sini. Bagiku, kota ini seperti buku kosong yang boleh kutulis ulang sesuka hati. Tidak ada bab masa lalu yang menghantui, tidak ada nama yang mengusik, tidak ada luka lama yang menetes lagi. Semuanya baru, segar, murni.
Aku tahu, aku tak mungkin selamanya di sini. Pada akhirnya aku harus kembali ke tempat di mana aku dikenal, di mana namaku dipanggil, dan di mana aku punya peran yang harus dimainkan. Tapi sebelum hari itu tiba, izinkan aku menikmati sejenak rasa anonim ini. Rasanya seperti menghirup udara pertama setelah lama tenggelam. Seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Seperti senyum asing yang terasa lebih hangat dari pelukan orang terdekat.
Jika suatu hari nanti aku kembali, mungkin aku tak akan dikenang oleh kota ini. Malang tidak akan mengingat langkah-langkah kecilku di trotoarnya, atau tatapanku pada langit senjanya. Tapi itu tak apa. Yang penting, aku akan selalu mengingat kota ini sebagai ruang sunyi yang penuh keramaian, sebagai tempat di mana aku kembali menemukan diriku sendiri.
Dan malam ini, ketika lampu jalan berpendar lembut, aku menutup catatan ini dengan satu kesadaran: tidak ada yang benar-benar spesial di kota Malang, tapi justru karena itu, aku merasa spesial bisa singgah di dalamnya.
Malang, 30 Agustus 2025
Share this content:


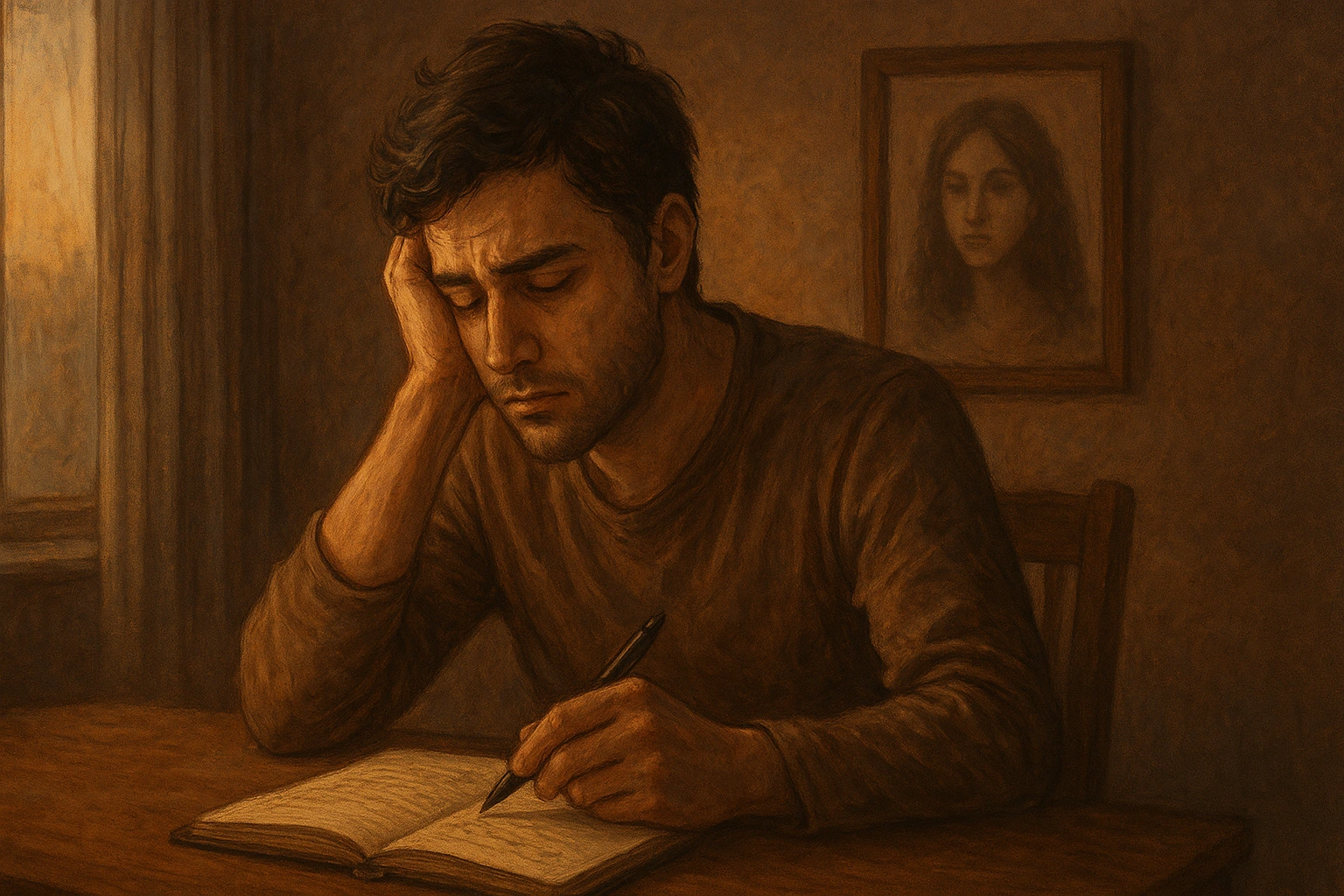
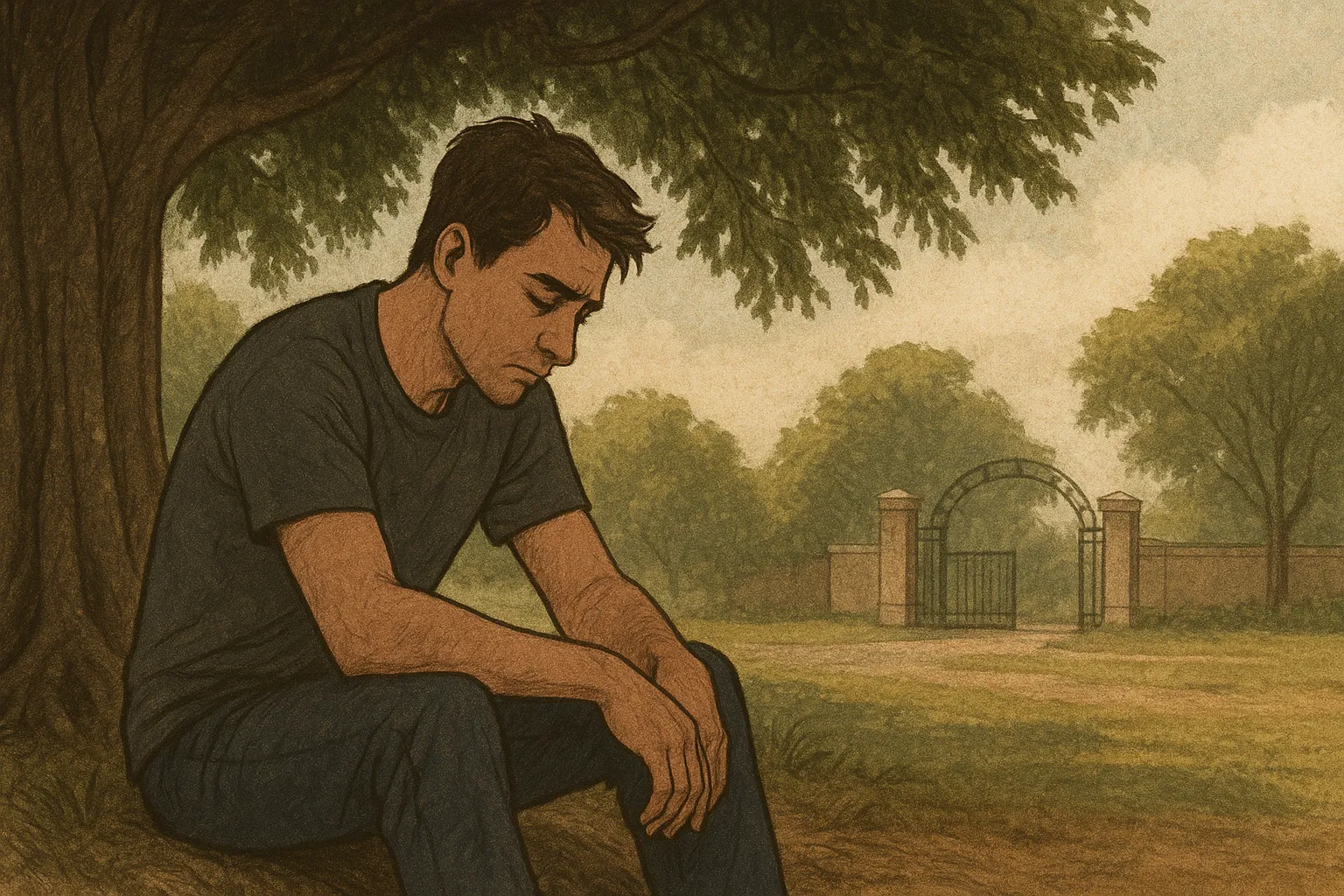










Post Comment