My Diary Chapter 12 : Budug Asu
Hai,
Aku kembali lagi. Seharusnya aku menulis ini minggu kemarin, tapi tak apa, ya? Waktu kadang seperti angin yang berhembus diam-diam—tak terasa, tiba-tiba saja ia sudah jauh meninggalkan jejak. Minggu lalu terlalu cepat berlalu, seperti aliran sungai yang tak pernah mau menunggu siapa pun. Tapi aku pikir, tak ada kata “terlambat” untuk mengabadikan kenangan, bukan? Karena pada akhirnya, kenangan bukan tentang seberapa cepat ia dituliskan, melainkan seberapa dalam ia tertanam dalam hati. Jadi, hari ini aku menulisnya… perjalananku minggu kemarin. Mungkin bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah serpihan biasa dari hari-hari yang lewat, mungkin terdengar membosankan dan tak berarti. Tapi bagiku, setiap langkah, setiap napas, setiap detik yang kuhabiskan dalam perjalanan itu… adalah cerita yang layak kusimpan rapi dalam lipatan waktu.
Minggu kemarin, seperti biasa aku berlari. Tapi kali ini sedikit berbeda. Aku tidak hanya berlari mengitari kota, melewati jalanan yang sudah terlalu sering kuhafal lekuknya, atau trotoar yang terlalu akrab dengan tapak kakiku. Tidak. Kali ini aku memilih jalan yang lebih sunyi, lebih tinggi, lebih menantang. Aku memutuskan untuk berlari ke dataran tinggi—ke bukit, atau gunung? Ah, apalah namanya, keduanya sama-sama menjadi pelukan alam yang luas dan menenangkan. Tepatnya, aku pergi ke Bukit Budug Asu. Aku rindu… benar-benar rindu pada suasana pegunungan yang tenang. Seperti rindu pada pelukan yang tak pernah datang, tapi selalu kurindukan. Jadi aku putuskan: ke puncak saja, biarkan kakiku menapaki tanah tinggi, biarkan paru-paruku mencium aroma embun pagi yang belum tersentuh polusi kota.
Baca Juga : My Diary Chapter 11 : Terjebak
Awalnya, aku ingin ke Bukit Jabal. Namun, nasib berkata lain—jalurnya sedang tutup sementara. Sejenak aku diam, tapi bukan berarti menyerah. Seperti air yang selalu menemukan celah di antara bebatuan, aku pun mencari jalan lain. Dan Budug Asu menjadi jawabannya. Tak ada kekecewaan, justru ada semacam getar kecil di dada, seperti perasaan saat akan bertemu seseorang yang sudah lama tidak jumpa. Aku tahu, di sana ketenangan menungguku.
Aku berangkat setelah salat Subuh. Langit masih biru tua, perlahan menjingga, seperti kain langit yang sedang disulam oleh jarum mentari. Aku tak langsung berlari. Pertama-tama, aku naik motor ke Asah Singosari, Kabupaten Malang. Dari sana barulah aku mulai berlari ke arah Budug Asu, melewati jalur pendakian via BBIB Singosari. Kau tahu? Udara pagi waktu itu… sungguh menampar wajahku dengan kelembutan. Tidak seperti dingin kota yang menusuk dan membuat resah, dingin di sini seperti belaian ibu yang menenangkan anaknya. Kicauan burung terdengar seperti paduan suara alam, menyanyikan lagu penyambutan untuk setiap pendaki yang datang. Desiran angin melintas di antara dedaunan, berbisik pelan seolah menyampaikan rahasia langit. Dan ketika matahari mulai mengintip malu-malu dari balik perbukitan, langit berubah menjadi kanvas jingga yang luar biasa indahnya. Seindah senyummu… ah, iya, aku sempat mengingatmu waktu itu. Entah kenapa, langit pagi sering kali mengingatkanku padamu—tenang, hangat, dan menenangkan.
Baca Juga : My Diary Chapter 10 : Hati yang Tertinggal
Aku mulai berlari dari bawah, melewati BBIB, terus ke arah parkiran Budug Asu, lalu naik ke basecamp. Dari basecamp, aku lanjutkan perjalanan menuju puncak lewat jalur pendakian yang, jujur saja, cukup menantang. Jalurnya terjal, menanjak, terkadang licin oleh embun yang jatuh semalam. Tapi setiap langkah terasa seperti percakapan sunyi antara aku dan alam. Tak ada keramaian kota, tak ada klakson, tak ada kebisingan. Hanya detak jantungku yang berdentum seperti genderang semangat, dan napasku yang membentuk kabut tipis di udara pagi. Setiap langkah membawa aku semakin dekat dengan langit. Di beberapa titik aku berhenti, bukan karena lelah semata, tapi karena aku ingin menikmati pemandangan yang terbentang di depan mata—pemandangan kota yang tampak kecil dari kejauhan, gunung Arjuna yang berdiri gagah di kejauhan seperti penjaga abadi, dan hamparan kebun teh yang hijau menghampar sejauh mata memandang. Naik lebih tinggi lagi, aku melewati kebun kopi dan jajaran pohon pinus yang menjulang seperti tiang-tiang penopang langit. Di sana, hidup terasa begitu sederhana. Tak ada hiruk-pikuk, tak ada pertengkaran, tak ada bising. Hanya aku, alam, dan kesunyian yang damai.
Aku sering ditanya, kenapa aku begitu mencintai gunung? Jawabanku selalu sama, meski dalam hati, jawabannya lebih luas dari sekadar kata. Gunung… selalu menenangkan. Ia seperti pelukan sunyi yang tak pernah menuntut apa-apa. Ia tak bertanya siapa aku, dari mana aku datang, atau apa yang sedang aku hadapi. Gunung hanya diam, tapi diamnya bukan hampa. Diamnya adalah keheningan yang menyembuhkan. Di kota, manusia saling mencaci, saling sikut, saling berlomba dalam hiruk-pikuk yang melelahkan. Tapi di gunung, bahkan orang asing pun saling menyapa. Satu “halo” dari sesama pendaki terasa seperti pelukan kecil yang hangat. Tidak ada kepura-puraan. Semua sederhana.
Baca Juga : My Diary Chapter 9 : Mendung
Kalau bicara soal gunung dan laut… aku selalu punya jawaban yang mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Gunung selalu menenangkan. Laut… terlalu berisik. Suaranya seperti jeritan rindu yang tak tahu ke mana harus pulang. Tapi jangan salah, aku tidak pernah membenci laut. Bagiku, laut adalah tempat yang istimewa, bukan karena aku menyukainya, tapi karena di sanalah seseorang yang aku kagumi menemukan kebahagiaannya. Dia… yang namanya masih abadi dalam hati, meski waktu telah berlari sejauh ini. Dia, yang hingga kini masih kusebut dalam doa setiap malam, dengan harapan kecil yang kusembunyikan rapi di antara helaan napas panjang: semoga suatu hari nanti, kami bisa dipertemukan kembali. Bukan sebagai kenangan yang menggantung, tapi sebagai takdir yang akhirnya bersatu.
Di puncak Budug Asu, aku berdiri lama. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah, rumput, dan pohon pinus. Aku menutup mata, membiarkan angin itu menyapu wajahku. Dalam diam, aku berbicara pada langit. Aku bercerita tentang rasa lelahku, tentang rindu yang tak pernah benar-benar hilang, tentang kenangan yang masih membekas kuat. Aku bercerita pada langit, karena langit tak pernah menghakimi. Ia hanya mendengar, seperti kamu dulu, saat aku bercerita panjang lebar tentang segala hal, dan kamu mendengarkannya dengan mata yang penuh perhatian.
Baca Juga : My Diary Chapter 8 : Rintik Rindu
Perjalanan turun tak semenantang saat naik, tapi rasanya lebih syahdu. Seperti langkah seseorang yang berjalan pulang dengan hati tenang. Aku menoleh beberapa kali ke belakang, ke arah puncak yang semakin jauh. Ada perasaan aneh—campuran antara puas, tenang, dan sedikit sendu. Seolah aku meninggalkan sepotong hatiku di sana, di antara kabut pagi dan desiran angin.
Mungkin bagi orang lain, kisah ini tak penting. Hanya cerita lari pagi ke bukit. Tapi bagiku, ini lebih dari sekadar lari. Ini adalah perjalanan batin. Perjalanan untuk menemukan kembali ketenangan yang sering hilang di tengah riuhnya hidup. Perjalanan untuk berbicara dengan diri sendiri tanpa gangguan. Perjalanan untuk mengingatmu, tanpa air mata.
Dan kini, saat aku menuliskannya, aku merasa damai. Seperti langit setelah hujan—jernih, bersih, dan penuh janji akan hari yang baru. Entah bagaimana hidup akan membawaku esok, entah ke gunung mana lagi langkahku akan pergi, entah ke laut mana takdir akan menuntunku. Tapi satu hal yang pasti: setiap langkahku selalu menyimpan cerita. Dan hari itu… di Bukit Budug Asu… adalah salah satu cerita yang akan selalu kuingat—bukan hanya karena pemandangannya, tapi karena di sana aku belajar: ketenangan bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang dirasakan… dalam diam.
Malang, 07 Oktober 2025
“Gunung tak pernah berbicara, tapi dalam diamnya, aku menemukan jawaban yang tak bisa diberikan oleh keramaian kota. Di puncaknya, aku berdialog dengan langit—tentang rindu, tentang tenang, dan tentang kamu yang masih abadi dalam doa.”











Share this content:
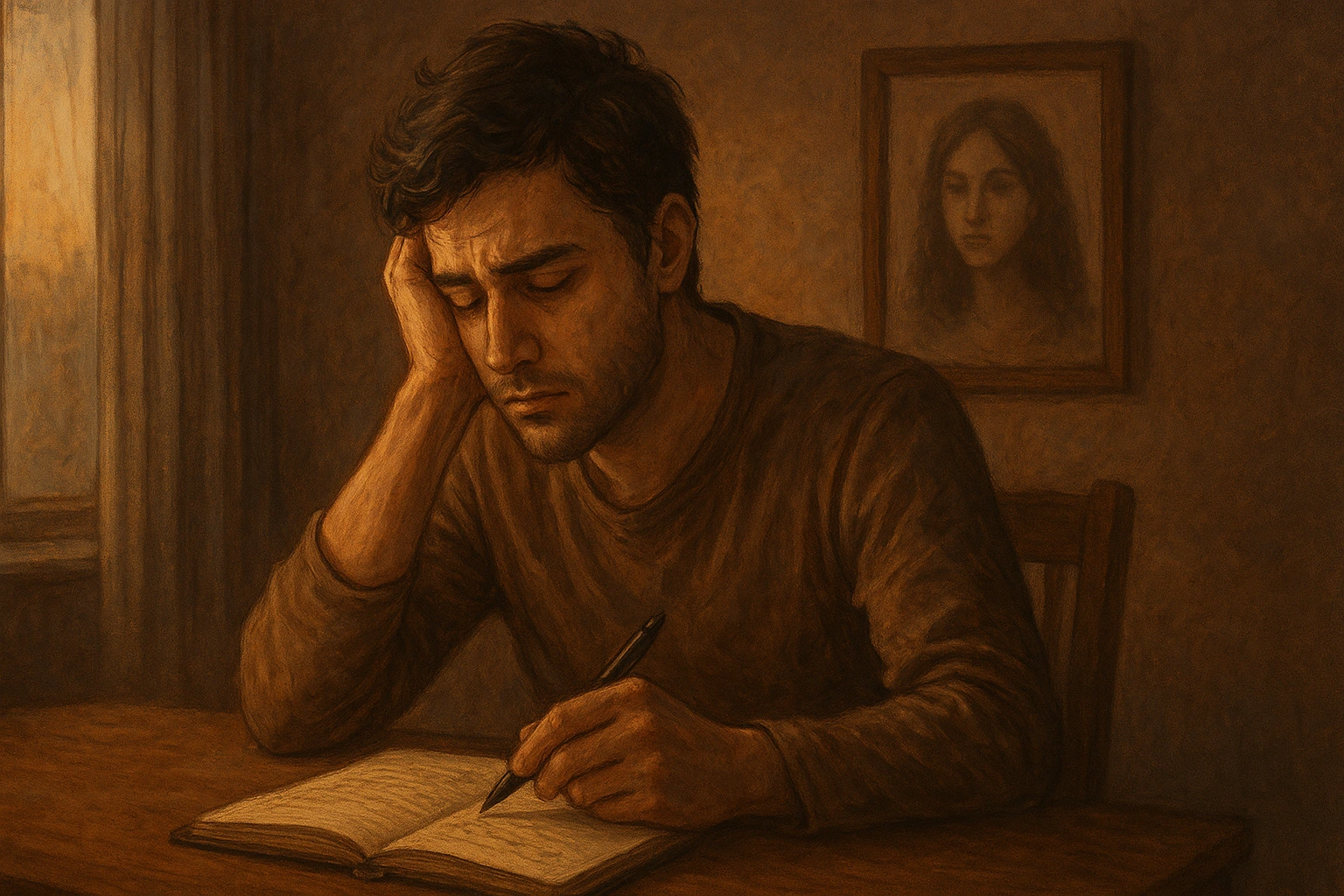
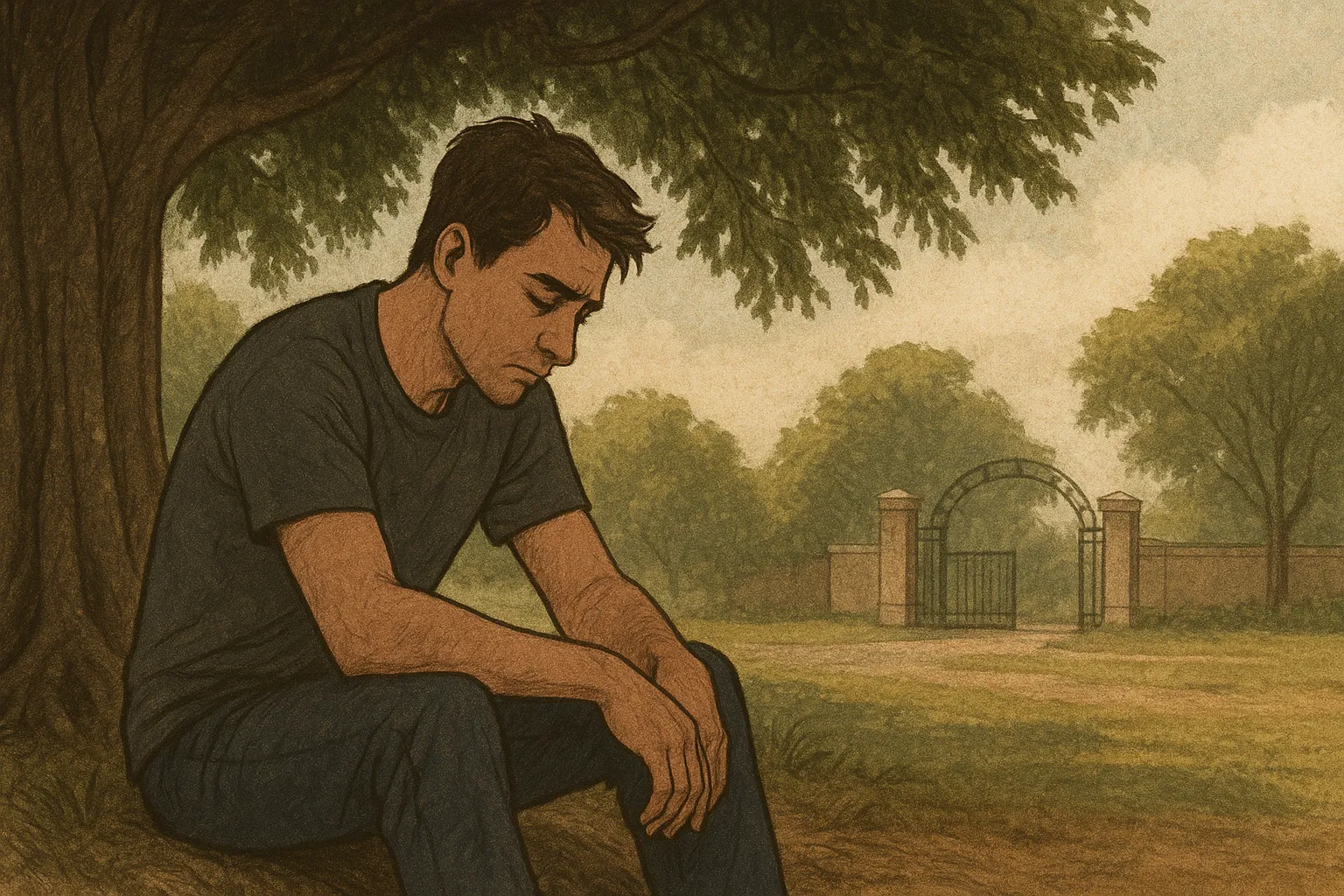











Post Comment