My Diary Chapter 8 : Rintik Rindu
Story Edelweiss – Hari ini aku ingin menulis sesuatu, di sela rintik hujan yang jatuh di luar toko kecilku di Malang. Malang selalu punya cara aneh untuk menahan langkah waktu. Di sini, setiap tetes hujan seperti menggandakan gema kenangan, dan hari ini, entah mengapa, gema itu berwujud dirimu. Hujan mengetuk pelan atap seng, seperti mengetuk ruang-ruang sepi dalam dadaku, dan aku pun mengizinkan ingatan yang selama ini kutahan untuk menetes bersama. Mungkin aku memang bodoh, masih saja menulis untuk seseorang yang entah sedang apa di tempat lain, entah masih memikirkan hal yang sama atau sudah jauh berjalan ke arah yang tak lagi ada aku. Tapi bukankah itu yang membuat kenangan begitu setia? Ia tak menunggu jawaban, hanya menunggu untuk diakui keberadaannya.
Hari ini, aku kembali ke awal cerita—atau setidaknya, ke awal yang sempat kita miliki. Aku ingat, hujan pertama yang mempertemukan percakapan kita lagi setelah sekian lama seperti dua benua yang terpisah samudra. Malang kala itu diselimuti gerimis yang lembut, seolah alam tahu, pertemuan tak selalu harus keras dan dramatis. Kita memulai ulang dengan kata-kata sederhana, semacam “Hai, apa kabar?” yang mungkin bagi orang lain terdengar biasa saja, tapi bagiku itu seperti kunci yang membuka pintu dunia lama, dunia di mana kau pernah menjadi pusat orbitku. Bahkan hingga sekarang, setiap kali mendengar suara hujan di atap, aku seperti mendengar suaramu yang dulu selalu membawa kehangatan yang ganjil, seperti secangkir teh panas yang menunggu di meja kayu beraroma tanah basah.
Baca Juga : My Diary Chapter 7 : Kilometer Rindu
Aku masih bisa merasakan sensasi saat itu: kamu di sana, aku di sini, dan jarak yang entah mengapa justru membuat kita begitu dekat. Seolah-olah jarak memberi kita ruang untuk saling mencari tanpa tergesa, seperti dua burung yang terbang di langit luas, tahu mereka akan bertemu di satu arus angin yang sama. Kau masih ingat, kan, saat aku bercerita tentang hujan—tentang awan yang seperti kapas terbakar jingga senja, tentang angin yang membawa wangi daun basah? Kata-kata receh, katamu waktu itu, tapi kau mendengarnya dengan antusias seperti mendengar dongeng masa kecil. Dan aku, yang jarang merasa didengarkan, menemukan rumah kecil dalam setiap responmu.
Ada satu sore yang tak pernah hilang dari ingatanku. Saat itu hujan turun dengan irama yang nyaris sempurna, seperti melodi rahasia yang hanya kita pahami. Kau meminta video singkat hujan dari tempatku. Katamu, kau ingin membuat sesuatu darinya. Aku mengirimkannya tanpa banyak tanya, karena bagiku, itu semacam permintaan suci. Lalu, beberapa saat kemudian, kau mengirim balik video estetik buatanmu—potongan-potongan hujan yang kusorot, kau rajut jadi karya kecil yang membuat dadaku hangat. Lagu yang kau pilih masih terngiang jelas: “Kan kukenalkan, penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja.” Waktu itu, aku merasa seperti sedang berdiri di bawah payung yang sama denganmu, meski jarak ribuan kilometer membentang di antara kita. Kau berhasil membuat jarak menjadi puisi, dan aku… aku jatuh semakin dalam pada apa pun yang kita jalani, meski tak pernah kita beri nama.
Baca Juga : My Diary Chapter 6 : Tentang Gunung dan Lautan
Kini, bertahun kemudian, aku duduk lagi di kota yang sama, menatap hujan yang sama, tapi tanpa pesan darimu. Hanya pikiranku sendiri yang sibuk menafsirkan sisa-sisa kenangan. Aku bertanya-tanya, apakah kau masih menyimpan video itu? Apakah lagunya kadang masih terputar diam-diam di playlistmu, atau sudah tergantikan oleh ratusan nada baru? Mungkin tidak. Mungkin semua itu telah kau simpan rapi di laci terdalam ingatanmu, atau mungkin sudah kau biarkan hanyut bersama arus waktu yang tak bisa kita lawan. Namun, seperti hujan yang selalu kembali meski musim berganti, ingatan itu kembali padaku. Setiap tetesnya mengandung wajahmu, tawa kecilmu, cara kau menatap dunia.
Ada yang unik dari cinta yang tak pernah benar-benar bersatu secara fisik. Ia seperti kabut yang melayang di antara dua puncak gunung: tak bisa digenggam, tapi terasa di kulit, menyejukkan, memeluk tanpa menyentuh. Kita adalah kabut itu. Kita saling mencari meski tahu takdir sudah menulis garis pemisah. Kita saling memberi, bahkan ketika jarak adalah jurang yang tak mungkin diseberangi. Aku sering berpikir, mungkin cinta seperti ini adalah cinta yang paling jujur. Tanpa kepemilikan, tanpa tanda tangan di kertas apa pun, tanpa rutinitas yang menumpulkan rasa. Cinta yang berdiri sendiri, seperti hujan yang jatuh hanya karena langit tak bisa lagi menahannya.
Baca Juga : My Diary Chapter 5 : Sebuah Perenungan
Kadang aku ingin marah pada diriku sendiri karena masih saja menunggu. Tapi menunggu apa, sebenarnya? Aku tidak menunggu pesan darimu. Aku bahkan tidak menunggu kehadiranmu secara fisik. Yang kutunggu, mungkin, hanyalah momen kecil ketika kenangan itu menelusup tanpa izin, memberi tahu bahwa aku pernah dicintai, meski caranya tak seperti kisah-kisah biasa. Mungkin aku menunggu kesempatan untuk terus menulis tentangmu, agar kenangan ini tetap bernapas. Menulis adalah caraku mengabadikanmu, seperti hujan yang mengabadikan aroma tanah.
Di luar sana, hujan mulai reda. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kopi dari warung tetangga. Kota ini diam, hanya sesekali motor melintas meninggalkan jejak air di jalan. Malang seperti menyimpan rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah jatuh cinta di bawah langitnya. Aku berjalan keluar toko, menatap matahari sore yang memantulkan cahaya kuning lembut di genangan air. Dalam pantulan itu, aku seolah melihat siluet kita: dua bayangan yang nyaris bersentuhan, tapi tak pernah benar-benar menyatu. Dan anehnya, bayangan itu membuatku tenang. Ada keindahan dalam keterpisahan yang kita jalani.
Baca Juga : My Diary Chapter 4 : Jejak Kaki di Kota Malang
Aku ingin menulis pesan sederhana: Hai, kamu sedang apa di sana? Bolehkah aku bilang kalau aku rindu? Tapi aku tahu, pesan itu akan mengapung tanpa arah. Jadi, aku biarkan saja kata-kata ini tinggal di buku harianku. Mungkin suatu hari, entah bagaimana, semesta akan menyampaikannya padamu lewat angin, atau lewat hujan yang menetes di atap rumahmu. Mungkin kau akan menengadah dan merasakan sesuatu yang asing tapi akrab, seperti debar lama yang tak sepenuhnya hilang.
Kau tahu, rindu ini aneh. Ia bukan rindu yang memaksa pertemuan, bukan rindu yang menuntut jawaban. Ia hanya rindu yang ingin diakui, seperti bunga liar yang tumbuh di celah trotoar, indah tanpa perlu dipetik. Aku tidak ingin merusak apa yang pernah kita miliki dengan harapan-harapan yang tak realistis. Cukup bagiku untuk tahu bahwa pernah ada seseorang di suatu tempat, yang mendengarkan cerita hujanku, yang membuat video dari potongan realita kecil yang kuabadikan, yang membuatku merasa penting tanpa harus memiliki.
Sekarang hujan benar-benar berhenti. Hari terasa lebih sunyi, tapi hatiku tidak lagi sepi. Aku menutup buku ini perlahan, seperti menutup pintu yang tak perlu dikunci. Karena aku tahu, di balik semua jarak dan waktu, kau tetap ada—bukan dalam genggaman, tapi dalam setiap detak yang mengerti bahasa hujan. Dan mungkin, hanya mungkin, itu sudah lebih dari cukup.
Share this content:


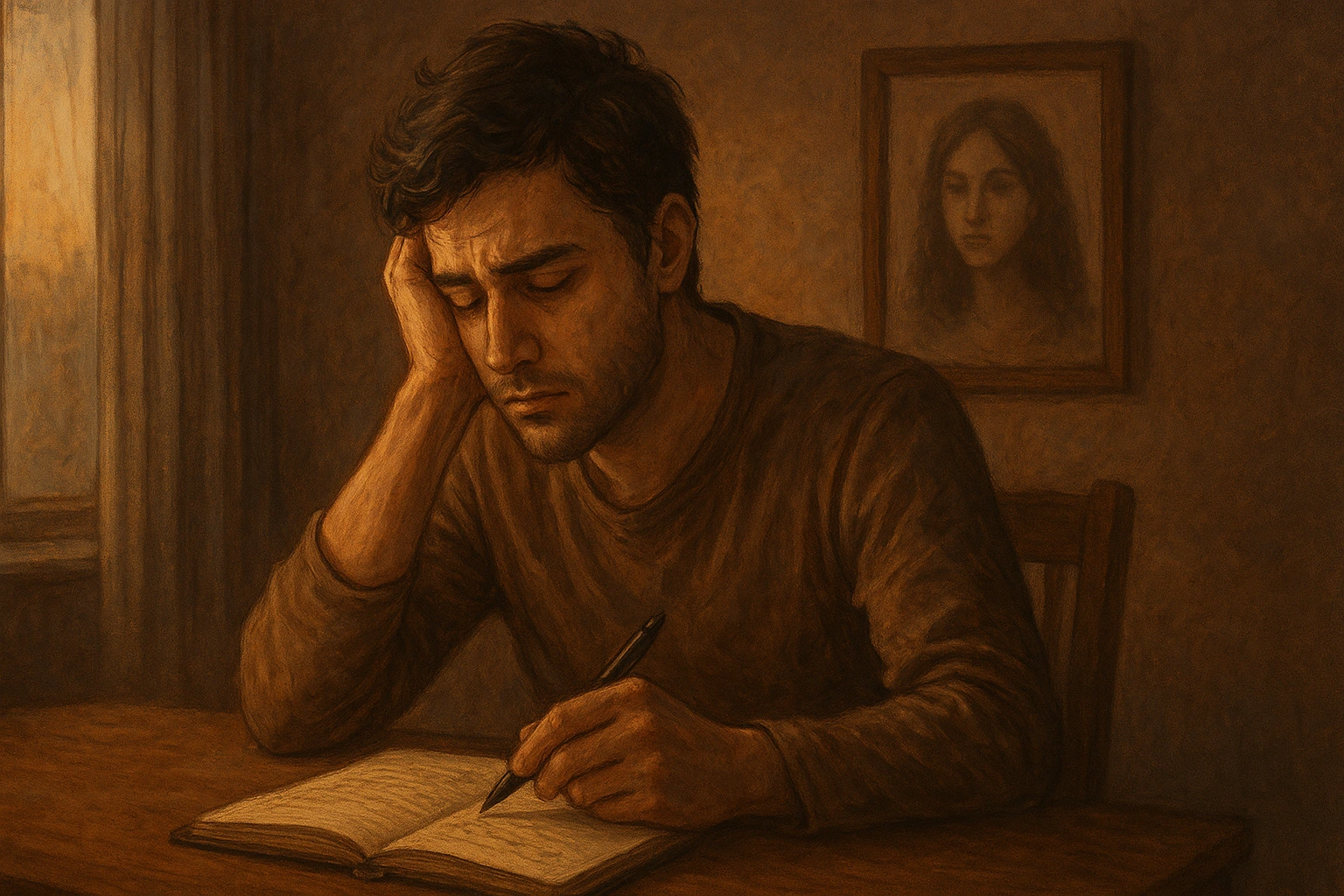
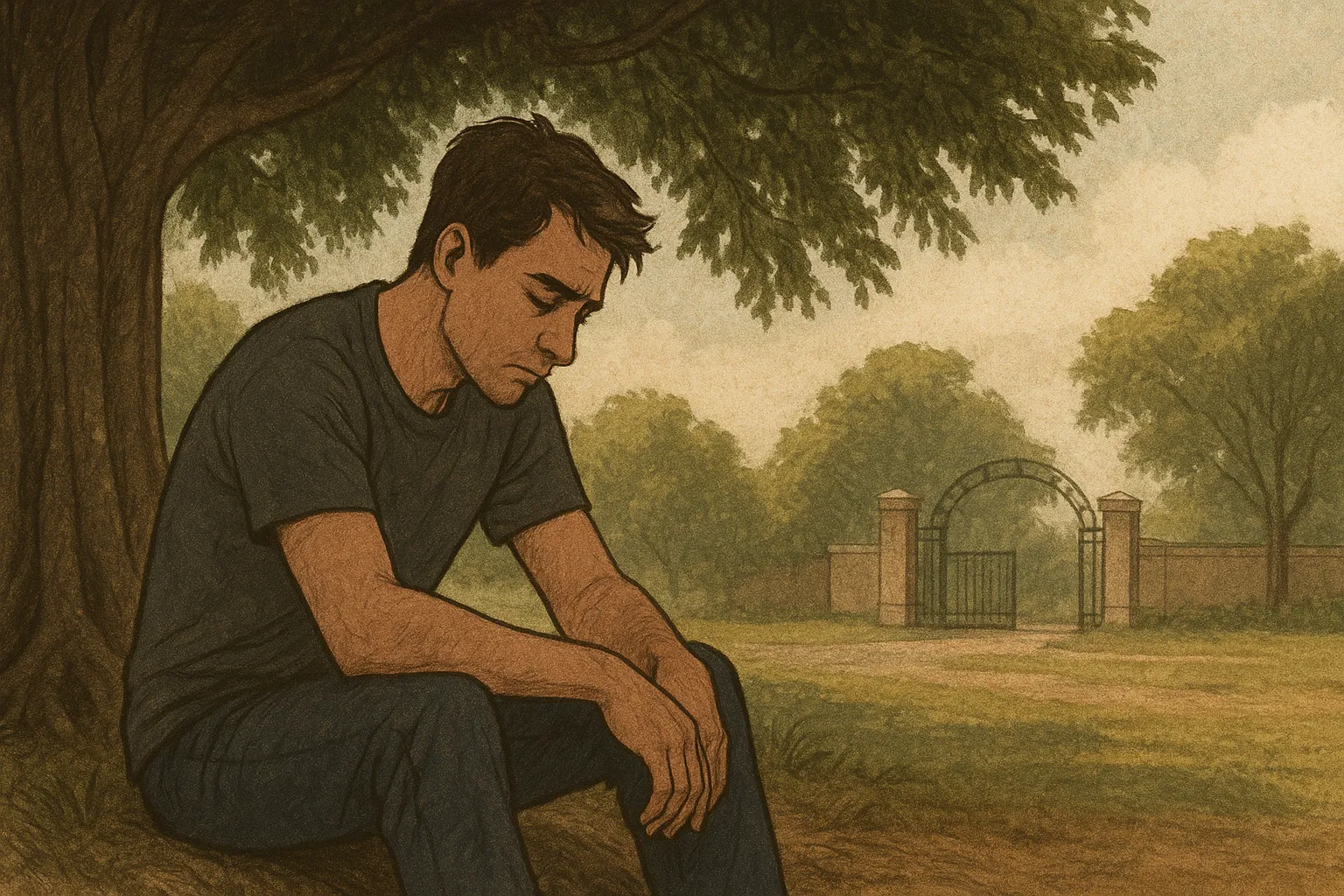










Post Comment